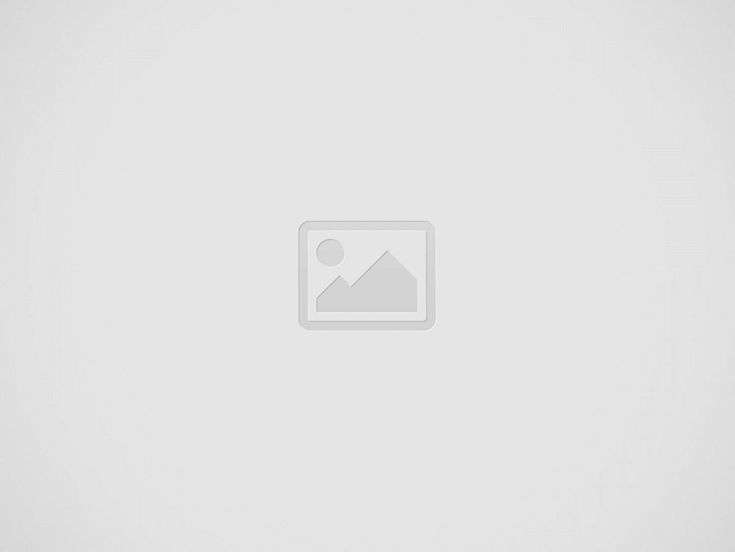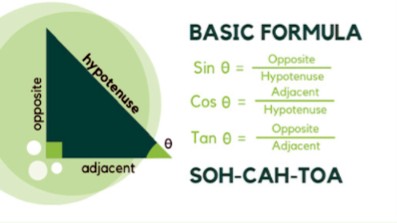Tak ada seorang anak sekolahpun di dunia ini yang tidak mengalami proses belajar mengajar dari rumah selama pandemi Covid 19.
Tulisan ini didasari atas pengalaman pribadi, pengamatan lingkungan sekitar, curhat rekan-rekan orang tua dan siswa-siswa dari berbagai sekolah, social media, maupun media online. Saya sangat yakin, dari survey yang katanya 3 juta guru dan hanya 2,5 % yang berkualitas itu, adalah banyak sekali rekan-rekan di sekitar saya. Namun sebagai refleksi diri, mungkin tulisan ini bisa membantu pola pikir rekan-rekan sekalian baik yang sudah melakukan serupa atau berbeda, untuk saling melengkapi. Karena kita guru adalah yang benar-benar terlibat dengan siswa, yang sebarisan dengan siswa, bukan hanya berbicara di forum sebagai pelatih guru atau bukan sebagai pengamat pendidikan yang cenderung bercakap pada sebuah usulan dan kritik.
Covid 19 memaksa setiap orang melakukan pengaturan jarak secara fisik. Pertemuan berkelompok yang mungkin paling besar adalah pertemuan di sekolah. Ya, anak-anak sekolah yang dalam satu kelas bisa terdiri dari 15 – 40 siswa. Waktu istirahat yang makan di kantin dan sebagainya. Itulah dari sejak awal pandemi ini ada di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, kegiatan nomer 1 yang dihentikan adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dimulai dari keputusan pemerintah daerah setempat, maka berlakulah pembelajaran dari rumah.
Pada saat ini akan terjadi, saya ingat medio Maret 2020, beberapa rekan guru dan orang tua memulai dengan kebingungan, beberapa siswa memulai dengan kegembiraan.
Mengapa guru bingung? Karena sebagian terbiasa dengan pola mengajar sangat tradisional. Bahwa pembelajaran hanya terjadi apabila ada tatap muka. Bahwa belajar harus fokus tidak boleh ada distraksi dari perangkat digital semacam “laptop” atau “telepon genggam”. Bahwa belajar harus runut sesuai RPP atau program tahunannya, dan setiap habis belajar siswa wajib menerima evaluasi.
Mengapa orang tua bingung? Karena sebagian orang tua berpikir dan berpendapat bahwa menyekolahkan anak-anaknya adalah sebagian kecil dari membagi tugas rutin pengontrolan anaknya. Beberapa orang tua mungkin harus jujur juga bahwa dengan sekolah 5 – 8 jam di luar rumah maka orang tua merasa ada sedikit “kebebasan” menjalankan tugasnya yang lain. Dengan kondisi anak-anaknya sekarang harus di rumah? Tentu tidak terbayang. Belum lagi orang tua yang punya motivasi perang ranking bagi anak-anaknya, wah bisa gagal nih cita-cita ranking 1-3.
Mengapa siswa gembira? Karena berpikir secara kebiasaan bahwa belajar itu adalah kegiatan di sekolah. Di rumah adalah beristirahat dan bermain.
Dan dimulailah masa-masa yang disebut sebagai “Home based Learning”, “Distance Learning”, “Remote Learning” dengan sebuah paradigma baru.
Banyak sekolah yang menerapkan belajar dari rumah ini sebagai memberikan tugas-tugas. Semoga tidak hanya tugas namun disertai dengan penjelasan. Namun bagaimana metodanya? Nah ini menarik karena metoda yang diyakini sebagai yang termudah dan tercepat adalah melalui video pertemuan. Dengan platform yang sangat gencar dipromosikan oleh agen-agen perubahan produk tersebut, maka cara mengundang siswa melalui video menjadi paling laris. Terjadinya pembelajaran pada saat video tadi dan para guru akan berharap siswa fokus mendengarkan dan memperlihatkan wajah melalui video. Jadi pola pikirnya sesederhana memindahkan kelas tradisional ke dalam layar komputer.
Lalu bolehkah para siswa, anak-anak itu merasa sungkan hadir di video meeting memperlihatkan ruang belajar pribadinya, kamar pribadinya? Apakah guru hanya berkata, tidak boleh malu, kalian punya kewajiban untuk belajar dan kami absen. Pernahkah melihat acara “Tonight Show” saat Desta menceritakan betapa anaknya tanpa video menjawab pertanyaan dengan lancar namun begitu di depan kamera, mendadak terbata-bata? Ataukah guru hanya berpatokan pada GNM (anak artis) atau MSJ (selebgram cilik), yang di depan kamera selalu cepat sekali beraksi dan pandai dengan memainkan mimiknya.
Apakah guru juga berpikir jika anak yang sudah besar, maka hal di depan kamera adalah lebih lumrah? Ingat saja, belum tentu, apapun ada kondisi anomali.
Apakah dengan pertemuan melalui video maka pembelajaran sudah lengkap? Dan cenderung menyalahkan siswa jika masih tidak mengerti, pokoknya benar-benar merasa seperti suasana di dalam kelas yang mana semua anak wajib punya pandangam satu arah ke papan tulis? Semoga minimal yang masih begini. Mulailah dengan menikmati berbagai metode mengajar. Teknik individual kadang lebih bermakna bagi siswa yang membutuhkan. Fleksibelkah guru-guru? Tetap dengan PR dan tugas yang harus dikumpulkan setiap hari? Setiap dua tiga hari sekali tergantung jam pelajaran?
Ingatlah, PR sebagai pekerjaan rumah, dan anak-anak ini setiap hari berada di rumah, jadi bolehlah kita pertimbangkan untuk memberikan berdasarkan jumlah, durasi maupun tingkat kerumitan.
Orang tua harus dilibatkan dong? Setuju. Orang tua sebaiknya duduk di sebelah anaknya saat pemetikan nilai. Sekaligus tanda tangan pakta integritas bagi anaknya. Lho? Iya biar anak sadar harus jujur dan tidak berusaha nyontek atau mencari jawabannya melalui chatting dengan teman atau pencarian di internet. Kalau orang tuanya tidak sempat, orang tua tidak perhatian terhadap anak. Kalau orang tua sudah tidak ada, kan ada wali siswa. Kalau orang tua mendadak ada kesulitan lain, tidak bisa pokoknya harus ditemani. Tiba-tiba saya bersyukur sekali bahwa anak saya telah lulus SMA tahun lalu.
Ya sudah, jangan merepotkan orang tua, siswa memakai kamera luar yang terhubung dengan video pertemuan, jadi guru dapat memantau situasi dan lokasi sekitar siswa yang sedang dipetik nilainya. Orang tua senang tidak direpotkan, guru senang bisa melihat kejujuran siswa, siswa senang bisa dilihat oleh gurunya. Eh, tunggu dulu, ini untuk kelompok siswa dan orang tua yang memiliki kemudahan fasilitas ya, memiliki kamera sekunder atau kamera telepon genggam yang bagus. Kalau tidak memiliki itu? Uhm, ya, kita akan pikirkan cara lain *o-ow*
Cara lain? Aha, cara membuka menutup soal dari platform e-learning. Nah ini efektif. Pertanyaan dibuka selama beberapa menit sesuai bobot soal, lalu siswa menjawab di selembar kertas (mata pelajaran dengan ada hitungan, misalkan), lalu upload ke e-learning, soal ditutup, pindah ke soal lain. Iya, menarik banget ini cara. Hanya faktor tidak memberikan kepercayaan sama sekali (zero trust) kepada siswa. Selama ini menghadapi siswa tukang berbohong maka harus mendapat perlakuan seperti ini. Lho? hmm.
Mari instrospeksi diri, di level manakah para guru berada?
Para siswa, apakah kalian menikmati suasana belajar dari rumah, alias tidak pernah memperdulikan panggilan email atau pesan dari gurunya? Pura-pura saja tidak tahu nanti tinggal beri alasan “saya kok tidak terima email ya?”. Lalu mengambek dengan bilang “saya tidak suka cara ini, saya mau dijelaskan bertemu muka. Ini bukan gaya saya.” Atau justru kalian ada di tipe yang menyambut suka cita bahwa inilah waktunya saya tampil karena biasa di kelas sering tertinggal, saya mau menunjukkan bahwa sekarang saya mampu berusaha. Atau kalian yang memiliki akademis sangat baik, dengan kebiasaan kalian yang selalu tepat waktu, menjadi tergopoh-gopoh dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan dikumpulkan secara online dengan batas waktu tertentu. 9 mata pelajaran artinya 9 tugas. 13 mata pelajaran artinya 13 tugas. Lalu kalian mengambil kesimpulan “aaaahhh kami ingin kembali ke sekolah, cara ini membuat gila dengan tugas tidak ada putus-putusnya.” Sabar ya, Nak 🙂
Secara umum kondisi belajar dari rumah ini memiliki kendala yang berbeda-beda. Bahwasanya seorang Menteri Pendidikan kemaren diberitakan terkejut menemukan kondisi di pedesaan yang tidak berlistrik dan memiliki akses internet. Bahkan ada guru yang di saat menjaga jarak ini, malah harus berkeliling antar kampung untuk memastikan siswanya belajar sesuai yang dia instruksikan. Kalau melihat secara global, iya, sulit sekali.
Satu hal yang saya pahami adalah bahwa di Indonesia khususnya, Menteri Pendidikan sudah memberikan surat edaran mengenai penyesuaian pengajaran, tidak wajib menyelesaikan satu silabus kurikulum, lalu mengajar dengan cara sesuai yang dipahami guru dan siswa, tidak perlu melakukan ujian tradisional seperti di dalam kelas. Saya pikir hal-hal tersebut sudah menggambarkan diberikannya sebuah “kebebasan” untuk berkreasi dalam porsi kita sebagai guru. Namun, masih banyak pula guru-guru mengeluh yang diwakilkan oleh para pengamat pendidikan, pejabat-pejabat organisasi guru, mengatakan bahwa guru kebingungan di lapangan musti melakukan apa, lalu didesaklah Kemendikbud untuk membuat kurikulum darurat karena guru cenderung berusaha menyelesaikan silabusnya.
Nah, di sinilah letak miskomunikasi dan mispersepsi. Sudah diberikan kebebasan tetapi masih minta diatur supaya guru tidak salah langkah. Terus terang lelah membaca berita seputar itu. Tapi sayapun tidak pada kapasitas mampu memberikan solusi.
Belum lagi, sekolah yang mengadaptasi kurikulum international, sama seperti UNBK, semua ujian akhir bersifat “high stake exam” sudah dibatalkan periode Mei-Juni ini. Maka dengan batal, marilah guru bereksplorasi sesuai dengan potensi guru dan siswa kita. Namun masih banyak pula guru dan sekolah dengan pola pikir tetap ujian secara tradisional. Boleh buat proyek, boleh buat portofolio. Ah, namun bagi guru tetap lebih mudah adalah ujian online. Kita butuh bukti (“evidence”), ya benar. Namun tidak pernah pernyataan bukti itu adalah nilai ujian bersifat “high stake”. Benar-benar perubahan pola pikir, bukan?
Sehabis mengajar, kalau tidak diujiankan, maka siswa tidak mau belajar. Jadi orang tua pun menuntut ada tes. Iya benar. Namun tes atau evaluasi tadi bisa dipakai yang bersifat formatif saja. Tapi bagaimana kalau ada yang berpendapat tetap harus sumatif? Silahkan, karena sumatif bukan melulu “high stake” tadi kan? Jika dalam kondisi normal seorang guru ada yang memberikan evaluasi setiap minggu, maka dalam kondisi tidak normal ini, mungkin jangan mempertahankan kebiasaan tersebut. Walau kebiasaan baik tetapi kondisi “new normal” ini membuat kita ditantang untuk melakukan semua jenis penyesuaian.
Banyak cara lama yang musti disesuaikan atau bahkan diubah. Jangan ragu untuk berubah. Jangan takut untuk merubah. Siapa tahu ini menjadi keadaan normal hingga beberapa tahun ke depan? Jangan kuatir dikatakan terlalu fleksibel oleh rekan-rekan guru lain atau dianggap merusak “tatanan” peraturan baku guru yang tidak pernah tertulis tetapi tersirat, karena yang paling penting di saat ini adalah anak-anak yang mau belajar. Belajar yang tentu beragam kemauan, ada yang 100% mau, ada yang 30% mau bahkan masih ada yang 0% mau. Tetapi anggaplah mereka semua mau. Sepakat kan? 🙂
Di kenormalan baru ini, tantangan bagi saya adalah, membuat siswa lebih tertarik belajar, bukan lebih tertarik dapat nilai saja. Ini sulit, budaya belajar di sekolah adalah demi penentuan peringkat sudah mendarah daging. Legitimasi pintar dan tidak pintar sudah menempel di benak semua orang dan lembaga pendidikan. Juara di SD, masuk SMP mudah, masuk SMA mudah, masuk universitas mudah, masuk kerja awal mudah. Sukses? Berpenghasilan tinggi dari nilai akademisnya? Itu yang bukan pegangan. Tetapi budaya kita sudah mengakar, semua diawali dari peringkat akademis.
Jadi, marilah kita belajar. Guru belajar, Siswa belajar, Orang tua belajar. Dalam porsi masing-masing. Selamat Belajar!