Sejak Maret 2020, dengan terpaksa semua sekolah memulai era di mana pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh. Sudah tidak ada tawar menawar lagi.
Banyak opini bahwa sekolah harus tetap berjalan, karena pendidikan tidak boleh terputus begitu saja, bukan? Wah, saya selaku salah satu pendidik di sekolah, setuju pakai banget, bahwa pembelajaran tidak boleh terputus. Secara ini pendidikan dan ini profesi profesional saya.
Pada saat “terpaksa” harus tetap menjalankan sekolah tadi, maka banyak opini, banyak argumen, mengenai bagaimana cara paling efektifnya. Berlomba-lombalah, para “pakar pendidikan” membagikan tips dan trik untuk kami para guru. Tentu saja, terima kasih atas masukan-masukannya. Begitu banyak, maka kita harus pandai-pandai menyesuaikan mana yang pas, cocok dan terbaik bagi siswa kita.
Salah satu yang menarik perhatian saya adalah opini bahwa mengajar siswa (fokus saya adalah di jenjang SMP-SMA) itu adalah harus melihat siswanya, seperti keadaan normal, bertemu di ruang kelas, di area sekolah dan berkegiatan belajar ataupun penilaian semua diupayakan selaras dengan keadaan normal tadi.
Pertemuan tatap muka secara online. Teknologi telah mempermudah kehidupan manusia. Sudah bertebaran teknologi video call, antar dua individu atau dalam sebuah grup sekaligus. Jadi sebagian berpikir bahwa ini akan memudahkan “perpindahan / pergeseran” pembelajaran dari sekolah ke rumah, “remote learning”.
Maka dimulailah “sekolah online” dengan berusaha sebaik mungkin memindahkan kegiatan sehari-hari di kelas ke dalam ruang tangkapan layar komputer / laptop dengan video konferensi. Guru dan siswa kedua pihak menyalakan kamera agar tatap muka tadi tetap berlangsung sama seperti normal.
Fokus kepada video konferensi dalam mengajar, mengakibatkan perdebatan antara kamera dinyalakan atau dimatikan.
Pembicaraan, diskusi dengan beberapa kalangan guru, rata-rata menginginkan kamera selalu dinyalakan selama mengajar.
“Bicara di depan layar komputer sendiri tanpa melihat wajah siswa, kok merasa seperti orang aneh, bicara sendiri”. Alasan ini paling banyak, apakah anda juga ada di sini?
“Dengan melihat siswa maka saya dapat tahu, dia memperhatikan pelajaran atau tidak”. Ini pun alasan cukup banyak terungkap. Hati-hati di sini, tips untuk bapak/ibu guru, jangankan wajah di depan kamera, wajah di depan kita saja siswa duduk di dalam kelas, pikirannya bisa menerawang dan tangannya coret-coret di kertas (menulis / menggambar).
“Saya merasa siswa harus melihat mimik wajah saya pada saat menjelaskan pelajaran agar mereka mengerti lebih cepat.” Aha, ini guru yang punya bakat menjadi seorang “entertainer”.
Masih ada beberapa alasan lain namun tiga di atas rasanya yang paling sering diungkapkan. Rekan-rekan guru sekalian, bagaimana dengan anda. Apakah ada di antara tiga di atas? Bebas saja kok.
Sekarang mari kita melihat sisi siswa. Siswa pun ada yang memiliki tipe “entertainer” tadi, dia suka sekali tampil dan berpose di depan kamera. Bakat, bagus sekali itu. Sementara ada siswa yang jengah menyalakan kamera karena berbagai hal. Latar belakang tempat siswa duduk di rumah agak berantakan, ada anggota keluarga lain yang lalu lalang, perasaan kurang nyaman memperlihatkan wajah ke kamera, dan hal – hal lain yang mereka sendiri susah untuk mengungkapkan.
Sebagai guru, apakah dengan “kekuasaan” yang kita miliki maka kita tinggal perintah “pokoknya harus nyala”? Tidak menyalakan kamera maka akan ada pengurangan nilai partisipasi kegiatan di kelas, bahkan pengurangan nilai sebuah penilaian akademis. Wah, semoga jangan ya :).
Prinsip memindahkan sekolah ke rumah maka harus ada pertemuan tatap muka, dan selanjutnya agar bisa menatap siswa maka kamera harus dinyalakan. Kamera yang dimatikan artinya tidak ada proses tatap muka, maka tidak ada persekolahan. Ini yang sebaiknya jangan sampai terjadi. Sukses tidaknya sebuah pembelajaran bukan ditentukan dengan kamera saling menyala baik guru dan siswa.
Namun saya menyadari, hasil dari pengamatan sekitar, pembicaraan dengan rekan-rekan, ungkapan guru-guru melalui media sosial, masih cukup sulit rupanya diterima oleh pemikiran guru dan sekolah bahwa tanpa kamera pun proses belajar masih bisa berlangsung.
Mengajak siswa terlibat saat pembelajaran berlangsung, banyak sekali alatnya, gratis maupun berbayar. Gratis misalnya dengan memanfaatkan papan tulis berbagi, dokumen berbagi, slide presentasi berbagi. Yang berbayar dan personal dengan siswa, misalnya ada pear deck, nearpod. Jadi keterlibatan itu bukan hanya harus melihat wajah saja, kan?
Edutopia mengeluarkan sebuah artikel berisikan strategi untuk membuat siswa yang sungkan menyalakan kamera menjadi berinisiatif menyalakan. Sisi menariknya, menambah informasi bagi kita untuk belajar strategi tersebut. Terutama jika sebagai guru, dirinya juga pandai sekali bercerita dan memecah belah suasana menjadi sebuah “entertainment” bagi siswanya. Namun, di sisi lain, bagi guru yang lebih pendiam, “straight forward”, akan kesulitan dan malah menjadi “garing” jika memaksakan melakukan “ice breaking” atau permainan di jam pelajarannya. Plus, strategi untuk menarik minat menyalakan kamera dengan permainan juga tidak dapat dikatakan sama dengan selama pembelajaran inti setelahnya, iya kan?
Hal yang menarik, sehari setelah ditayangkan artikel tersebut, Edutopia kembali menuliskan dalam lini masa twitternya bahwa jika ada guru-guru lain yang kesulitan dengan meminta siswa menyalakan kamera, silahkan saling berbagi cara lain (yang maksudnya bukan sekedar pemecah suasana dan permainan saja), dan mempersiapkan pengajaran tanpa kamera tadi. Di sini terlihat bahwa memang beberapa pihak mengajukan keberatan bahwa anggapan pembelajaran tanpa kamera menghasilkan hasil yang lebih rendah daripada dengan kamera menyala, sehingga seolah-olah perlu strategi membuat siswa menyalakan kamera.
Karena semua itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi kelas dan pelajarannya. Jika cukup dengan audio yang menyala dan media interaksi yang melibatkan siswa mampu membuat suasana kelas online kita menjadi hidup, maka mengapa harus menyalakan kamera? Saat anak-anak aktif bekerja di media seperti pear deck misalnya, mereka tidak butuh melihat wajah kita gurunya. Namun, guru dapat langsung menegur, menyela, memberi “feedback” pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Lebih seru, bukan? Semoga.
Dua contoh video, pembelajaran menggunakan peardeck. Contoh pertama, setelah metode “synchronous” di kelas, dilanjutkan dengan “asynchronous” untuk siswa yang ingin mereview sendiri.



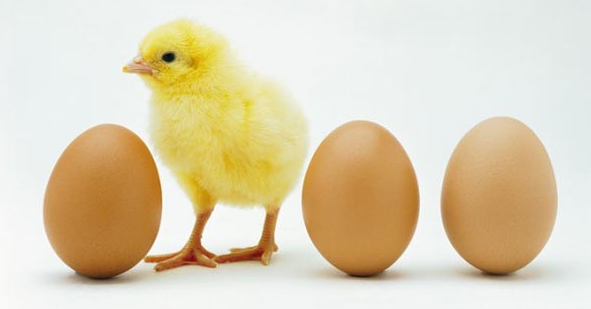


 .
. ), dengan konsekuensi berada di sekolah lebih lama dari waktu yang (awalnya) distandarkan sekolah, dan perlakuan semua mata pelajaran tersebut konon sama (untuk menghindari “kasta” mata pelajaran), jadi tugas tumpuk sana tumpuk sini, si siswa pun pandai untuk “mengakali” saja, sikap yang penting kumpul tugas menjadi prinsipnya sekarang. Guru konon hanya bisa kesal, mendapati siswanya “tidak mau belajar”, pokoknya guru kasih materi dua bab bahan UNBK belasan halaman, kasih tugas BI merangkum artikel, kasih daftar materi ulangan semester, kasih dan kasih. Siswanya? Entahlah mungkin sudah muntah, sudah bodo amat, bahkan ketika ada guru yang kesal siswa tidak memperhatikan, dan berkata “jika kamu tidak mau belajar, silahkan keluar, tersisa dua siswa saja di dalam kelasnya karena mereka kegirangan boleh keluar. Atau tetap di kelas mengerjakan tugasnya dan belajar karena suka. Bisa saja.
), dengan konsekuensi berada di sekolah lebih lama dari waktu yang (awalnya) distandarkan sekolah, dan perlakuan semua mata pelajaran tersebut konon sama (untuk menghindari “kasta” mata pelajaran), jadi tugas tumpuk sana tumpuk sini, si siswa pun pandai untuk “mengakali” saja, sikap yang penting kumpul tugas menjadi prinsipnya sekarang. Guru konon hanya bisa kesal, mendapati siswanya “tidak mau belajar”, pokoknya guru kasih materi dua bab bahan UNBK belasan halaman, kasih tugas BI merangkum artikel, kasih daftar materi ulangan semester, kasih dan kasih. Siswanya? Entahlah mungkin sudah muntah, sudah bodo amat, bahkan ketika ada guru yang kesal siswa tidak memperhatikan, dan berkata “jika kamu tidak mau belajar, silahkan keluar, tersisa dua siswa saja di dalam kelasnya karena mereka kegirangan boleh keluar. Atau tetap di kelas mengerjakan tugasnya dan belajar karena suka. Bisa saja.




