Sebagai seorang pendidik yang notabene adalah orang yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa, guru seringkali diidentikkan dengan orang yang harus baik, ramah, supel, menjadi pendengar, menjadi penasehat, menjadi tutor, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi segalanya bagi si siswa. Banyak guru mampu berperan super ganda seperti itu karena memang dia bertalenta banyak, tetapi banyak guru juga yang tergopoh-gopoh untuk mampu seperti itu dan banyak berkesan dipaksakan.
Karakter guru saja beragam, bertemu dengan karakter siswa juga lebih beragam, jumlah siswa jelas jauh lebih banyak. Sering sekali perbedaan karakter guru dengan siswanya menjadi boomerang bagi si guru maupun si siswa sendiri. Di sinilah mungkin dibutuhkan guru yang lebih berpengalaman dalam hal uji kesabaran, mungkin dibutuhkan untuk mengatasi karakter siswa yang beragam itu.
Hubungan guru dan siswa pun banyak sekali persepsinya. Ada yang berpendapat, guru harus gaul agar mampu mendekatkan diri dengan siswa, bisa jalan bareng siswa, bisa nonton bareng siswa. Ada juga, guru harus punya wibawa, biar dihargai dan dihormati siswa, jangan bergaul terlalu dekat dengan siswa nanti kewibawaan kita hilang. Ada juga yang di antaranya, guru harus gaul tetapi tetap menjaga kewibawaannya. Nah, tentu saja pilihan jatuh di tangan rekan guru sendiri, memilih yang seperti apa, asal tidak ada yang dipaksakan dan dibuat-buat.
Logika saya selalu memunculkan pendapat “untuk membuat pengaruh kepada siswa adalah bukan pada tindakan spektakuler apa yang harus dilakukan dan bukan pada kata-kata mutiara yang harus dikeluarkan”. Tetapi “ketulusan, niat, tindakan dan konsisten seorang guru” mungkin lebih membuat suatu perubahan kepada siswa.
Saya, merasa sebagai pribadi yang cukup terbuka, mau mendengar dan mau melihat latar belakang siswa, mau berkomunikasi dalam dunia / era mereka sekarang, “mau belajar” seperti mereka, tetapi mungkin bukan tipe yang bisa jalan-jalan, nonton bareng atau makan bareng dengan siswa (garing ah ngajak saya :p berasa beda umur #sadarusia).
Menengok ke tren pendidikan sekarang ini, salah satunya pendidikan berbasis IT sebagai salah satu skill abad 21, pendidik dan guru pun banyak yang sudah mengembangkan dan membekali dirinya dengan kemampuan IT dan memiliki banyak jejaring sosial serta blog pribadi.
IT is not out there, it is in here. Apakah guru ngeblog menjadi suatu tanda jika dia “up-to-date”? Mengerti teknologi dengan baik dan siap untuk hadir di pendidikan abad 21? Apakah guru yang nge-blog mempengaruhi gaya mengajarnya, media dan metode pengajarannya, interaksi dengan siswanya? Beberapa pertanyaan tersebut sering muncul di benak saya.
Hubungan “guru yang ng-blog” dengan “menjadi pendidik yang baik”, harus disepakati dan dipahami dulu sebagai dua hal yang berbeda (tetapi tetap berhubungan). Guru memiliki blog / situs yang dikelola dengan professional dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan siswa pembelajar adalah tujuan mulia. Guru yang hebat, terlahir dengan jiwa pelayanan yang luar biasa, tidak perlu mengidentifikasikan dirinya melalui sebuah blog tetapi dia sudah dicari dan dijadikan panduan bagi siswanya. Guru hebat bukan lagi digugu dan ditiru (saja) oleh muridnya (karena digugu dan ditiru masih edu 2.0 
Berada di lingkungan siswa yang kebetulan memiliki background cukup baik dan mengetahui dunia social media jauh lebih pandai daripada guru-gurunya tentunya banyak membuat gurunya minder, apalagi terus dibarengi dengan sikap guru yang malah memblok diri dengan mengatakan media dapat merusak siswa tanpa pernah mau memasuki dunia mereka adalah tindakan keliru dari seorang pendidik atau pengelola sekolah. Siswa memiliki blog? Hampir pasti iya karena tuntutan dari mata pelajaran bahasa (Inggris maupun Indonesia). Sebatas apakah mereka mengelola blog mereka? Rata – rata yang sebatas untuk membuat essay dan tugas pelajaran bahasa Inggris. Guru memiliki blog? “ah biasa, terus saya harus bilang wow gitu?” (mengutip bahasa gaul sekarang), rasanya mungkin itu ada di benak siswa saya saat saya memutuskan aktif di dunia blog melalui web yang saya kelola sendiri (geer nih :p).
Belajar itu proses, sering tidak terlihat di depan mata saat ini juga. Siapa dapat tentukan berhasil sekarang, setahun kemudian, lima atau dua puluh tahun kemudian? Suatu hari, saya menerima sms dari seorang siswa, memberitahukan alamat blognya. Di lain hari didatangi siswi kelas 7 dengan cerita-cerita lucunya dan alamat blognya. Rasanya hati ini senang sekali dan “lega” bahwa pemikiran saya selama ini tentang “menjadi konsisten” dan “mau belajar” (belajar menulis, belajar mengenal dunia social media mereka, belajar menggunakan software pembelajaran kreatif) adalah pengaruh yang besar untuk usia remaja mereka (semoga “kejutan-kejutan” itu tidak akan pernah berhenti, perihal mereka ikutan punya blog, itu hanya salah satunya).
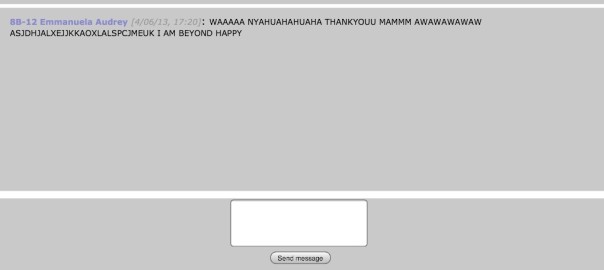

 )
)




