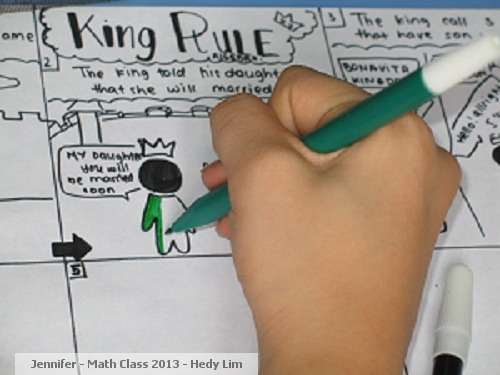Tanyakan kepada anak didik kita, bagaimana sih kriteria guru favorit untuk kamu? 
“Tidak suka marah-marah, pokoknya baiiiikk banget”
“Tidak suka kasih PR”
“Ulangannya jarang-jarang kalau perlu nggak usah ada ulangan”
“Free…..time……”
“Cara mengajarnya enak”
Dari lima pilihan siswa di atas, yang mana yang paling relevan? apakah argumen si guru akan “Tergantung kita bertanyanya kepada siswa yang tipe bagaimana? Semua siswa sih kalo bisa tidak ingin belajar” 
Pernahkah terlintas di dalam pikiran rekan pendidik bahwa sebenarnya siswa kita itu tahu persis bagaimana “memfavoritkan” gurunya? Kadang kita yang bisa saja kurang menyadari hal tersebut. Apalagi jika ditambah dengan asumsi bahwa pendidik “lebih berkuasa” daripada “anak didiknya” dan apapun yang siswa katakan belumlah dapat dikategorikan akurat kalau belum kita yang menyetujui. Ironis? Yahh itu kan pendapat saya.
Bagaimana menjadi guru yang favorit di mata siswa?
Menurut saya: Menjadi diri sendiri …dan bukan berpura-pura menjadi orang lain.
Tetapi, apakah penting label favorit untuk rekan-rekan seprofesi saya?
Pasti ratusan pendapat akan terlontar jika hal ini ditanyakan kepada rekan-rekan sekalian.
Salahkah menjadi seorang guru yang difavoritkan?
Tentu saja tidak ada yang salah sepanjang kita menjadi seorang pendidik yang menjalankan tugas keprofesionalannya dalam track / jalur yang benar.
Apakah wali kelas hampir pasti menjadi guru favorit siswa di kelasnya?
Atau malah sulit menjadi favorit karena wali kelas cenderung yang paling memperhatikan kerapian, kerajinan, keberhasilan kelasnya?
Bagaimana dengan guru yang berlindung di balik status “saya bukan wali kelas anak itu” (baca: sehingga saya tidak perlu terlalu memperhatikan siswa tersebut?) Opini – opini seperti itu tanpa disadari sering muncul di kalangan guru disertai dengan “anak si bapak A / anak si Ibu B”, “itu lho anakmu…” dalam merefer ke siswa yang punya “masalah”, “siapa dulu bapaknya / ibunya” jika merefer ke siswa yang “berpotensi baik secara akademis” 
Siswa adalah anak – anak. Mereka berada di usia yang pasti di bawah kita yang sudah menjadi pendidik, namun mereka sudah mulai belajar memandang dan menilai orang lain.
Sehingga, apabila siswa melihat gurunya sebagai orang yang baik, tegas, berwibawa, konsisten, memiliki konten dan dikunci oleh sosok yang sepadan dengan “panggilannya sebagai guru” maka hampir pasti diri si guru menjadi sosok yang dikagumi dan difavoritkan.
Tetapi seorang guru tidak perlu menjadi pribadi yang dikategorikan selalu ideal dalam menghadapi siswanya. Menjadi diri sendiri adalah kunci utama.
Lho, jadi ada guru yang bersaing untuk memperebutkan posisi terfavorit? *just kidding*
Salah satu yang saya sebut di atas adalah memiliki konten. Konten yang tentu saja disertai dengan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan siswa. Komunikasi sangat penting dimiliki oleh rekan-rekan yang mendedikasikan hidupnya dan menjalani panggilannya sebagai pendidik. Bukan pula berarti seorang pendidik yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertingginya (S2 atau S3) lalu jadi otomatis mampu berkomunikasi dengan baik terhadap siswanya. Seorang yang memiliki kemampuan di level komunikasi dengan siswa di jenjang SMA belum tentu bisa disamakan (dan tidak bisa diperbandingkan) dengan seorang yang memiliki kemampuan komunikasi terhadap siswa TK.
Lalu siapa lagi yang menilai kemampuan si guru dalam menjalankan tugas dan panggilannya tersebut? Jelas, institusi atau sekolah juga memegang peranan penting. Sekolah seringkali mendapat benturan dari pihak pengelola sekolah atau yayasan yang mewajibkan gurunya untuk memenuhi kriteria tertentu.
Sayangnya pemenuhan kriteria tertentu tersebut seringkali mengabaikan bakat lain yang dimiliki oleh si guru. Guru yang memiliki konten dan kemampuan komunikasi yang baik dengan siswa tetapi tidak mampu memenuhi tuntutan pengelola sekolah, dia menjadi guru yang tidak memenuhi standar.
Sebaliknya, mungkin juga ada institusi / sekolah yang karena kurang memiliki standar penilaian yang baik akan kemampuan dan kinerja gurunya, maka bisa saja si guru melakukan proses pembelajaran kepada siswanya tidak sebagaimana mestinya. Penyampaian materi yang bolong-bolong, evaluasi terhadap siswa yang “yang penting siswa senang”, dan yang terutama mungkin pembinaan karakter yang salah penyampaian karena si guru hanya demi “terlihat bagus dan benar menjalankan peraturan sekolah”.
Ada kalanya mungkin institusi sudah berusaha konsisten dengan segala kebijakannya, tetapi guru atas nama “demi siswa” tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Bisa “menjadi sebuah pokok bahasan besar” untuk hal tersebut.
Ironisnya, kembali ke judul awal saya guru favorit, guru yang di posisi itu malah mudah mendapatkan julukan tersebut.
Ada lagi karena demi menjalankan misi institusi sebagai sekolah berkualitas dalam mencetak prestasi akademis, seorang guru jadi ikutan hanya memandang kepada siswa yang memiliki bakat dan kemampuan akademis yang tinggi, lupa bahwa ada bagian siswa yang menjalankan kehidupan akademisnya dengan susah payah dan membutuhkan “bantuan seorang pendidik” yang mampu membuka dirinya “belajar untuk mau belajar pada subject yang sudah menjadi momok kesusahan bagi dirinya”, bukan melulu dijejal “ayo belajar supaya kamu bisa, kan kamu tahu kamu tidak mampu”. Manakah yang jadi favorit? Guru pintar yang mencetak siswa berprestasi akademis atau guru pintar yang mampu membuat siswanya mau belajar?  Silahkan juga dinilai sendiri.
Silahkan juga dinilai sendiri.
Jadi, guru menjadi favorit itu dari kacamata siapa ya? Murid? Yayasan? Kita sendiri?
Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Marilah menjadi diri kita sendiri dan menjalankan tugas kita sesuai dengan panggilan hati dan jiwa kita untuk melayani dan mendidik siswa kita menjadi siswa yang berkarakter, berbudi pekerti, dan memiliki kemampuan akademis yang baik